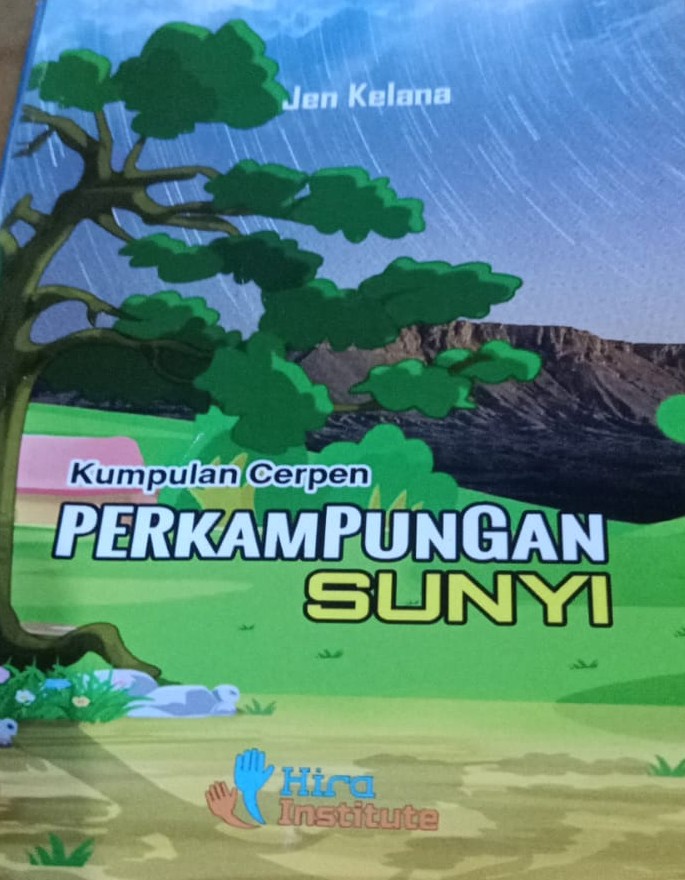Oleh: Asro Al Murthawy
Ada pepatah basi: “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.” Yang benar: guru adalah pahlawan dengan tanda tanya. Tanda tanya besar—kenapa profesi mulia ini sering diabaikan? Kenapa guru yang renta masih harus ngontel sepeda puluhan kilometer, sementara pejabat baru naik mobil dinas sudah minta jalan pakai sirene?
Itulah yang kutangkap dari kumpulan cerpen Perkampungan Sunyi karya Jen Kelana. Buku ini bukan sekadar kumpulan cerita pendek, tapi sejenis “rapor merah” buat kita semua.
Dan yang bikin pedas, penulisnya sendiri adalah seorang guru, dosen di Universitas Merangin, sekaligus anggota Sanggar Imaji Bangko—komunitas sastra yang sejak lama terkenal cerewet mengganggu kenyamanan kekuasaan di Kabupaten Merangin.
Coba baca cerpen Pak Guru Mukidi. Kisahnya sederhana: seorang guru tua tetap setia mengajar meski tubuhnya renta. Ia mengayuh sepeda dengan senyum, tapi akhirnya tumbang di jalan. Tragis, tapi real.
Lalu ada Masih Tentang Pak Guru, yang menyinggung tanah warisan raib gara-gara tanda tangan. Ada juga Orang Gila dan Cita-Citanya Menjadi Guru. Di sini satire benar-benar menohok: bahkan orang gila pun bercita-cita jadi guru, seakan profesi ini saking mulianya sekaligus saking terpinggirkannya.
Di tangan penulis lain, tema guru bisa jadi pamflet kaku. Tapi Jen Kelana pandai meracik. Ia menulis dengan gaya lembut, kadang puitis, tapi justru karena itulah kritiknya lebih menusuk. Cerita-ceritanya adalah kelas lain: bukan ruang dengan papan tulis, tapi ruang sastra yang membuat kita belajar jadi manusia.
Jangan lupakan latar belakangnya di Sanggar Imaji Bangko. Dari komunitas inilah lahir keberanian untuk menulis cerpen-cerpen “nggak sopan” pada realitas.
Lihat Kisruh—penuh nama absurd, Reksodikolo dan Brojodipuro, tapi jelas menyindir kekacauan sosial-politik kita. Atau Figura Tua, yang menggambarkan kerusuhan, perempuan glamor, rakyat marah, pejabat bobrok. Semua seperti panggung teater jalanan, di mana rakyat selalu jadi figuran.
Sanggar Imaji memang begitu: tidak ramah pada status quo. Dan Jen Kelana membawanya ke dalam buku ini. Hasilnya? Cerpen-cerpen yang terasa liar tapi tetap berakar di tanah Merangin, lengkap dengan pasar, kampung, dan bau comberannya.
Sebagai dosen, ia tak bisa menghindar dari kebiasaan berpikir berlapis. Cerpen Mimikri misalnya, bukan sekadar kisah, tapi alegori filosofis tentang terang, gelap, dan ilusi sosial.
Suatu Waktu menghadirkan dunia antara realitas dan kematian—absurd, tapi bikin kita mikir.
Di sinilah Jen Kelana membuktikan: ia bukan sekadar tukang cerita, tapi juga pengajar yang tahu bagaimana “mengaduk otak” pembacanya.
Cerpen yang paling bikin aku meringis adalah Ada Apa dengan Sirene. Seorang guru honorer pulang dari sekolah, cemas meninggalkan ibunya yang sakit. Di tengah jalan, ia terhambat konvoi pejabat dengan sirene meraung. Dan apa akibatnya? Tragis.
Ini bukan sekadar cerita. Ini sindiran keras: pejabat yang bangga dengan sirene adalah pejabat yang tuli. Mereka pikir rakyat akan kagum pada raungan itu, padahal yang terdengar adalah makian: brengsek!
Kelebihan buku ini jelas:
1. Autentik—lahir dari pengalaman guru, akademisi, dan aktivis komunitas.
2. Bahasa cair—kadang puitis, kadang satir, membuat pembaca ikut tersenyum getir.
3. Kaya lokalitas—kampung, pasar, dan tahlilan jadi latar yang hidup.
Kekurangannya?
• Beberapa cerpen terlalu pendek, lebih mirip fragmen ketimbang cerita utuh.
• Tema guru dan kritik sosial agak repetitif. Tapi siapa peduli? Justru repetisi itu seperti ketukan palu di kepala kita: “Hei, ini masalah serius, jangan pura-pura tuli!”
Buku ini menunjukkan bahwa Jen Kelana menulis bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk mengajar. Ia mendidik, tapi bukan di kelas dengan kapur dan papan tulis. Ia mendidik lewat sastra—yang kadang lebih jujur daripada buku teks.
Perkampungan Sunyi adalah buku yang menolak diam.
Ia bersuara tentang guru yang terpinggirkan, pejabat arogan, rakyat kecil yang terus digilas. Tapi suaranya tidak teriak-teriak. Justru karena itu, ia lebih tajam.
Maka kalau kau guru, bacalah ini sebagai cermin. Kalau kau mahasiswa, bacalah ini sebagai kuliah sastra yang gratis. Kalau kau pejabat doyan sirene, lebih baik jangan baca—takut nanti tersedak oleh suara sendiri.
Penulis tingal di Merangin dan menjabat sebagai ketua Dewan kesenian Merangin